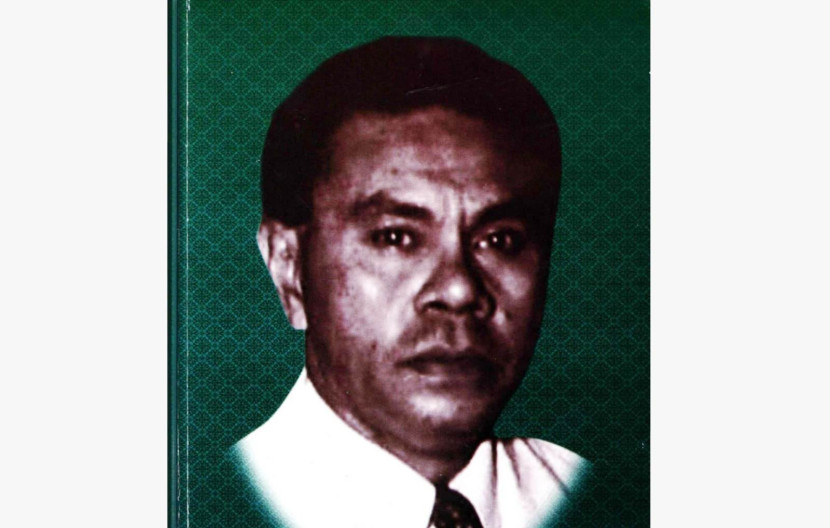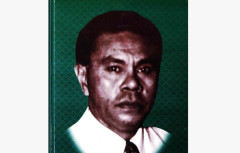Tujuh Kata di Piagam Jakarta Dihapus, Elson: Panik dan tak Perlu
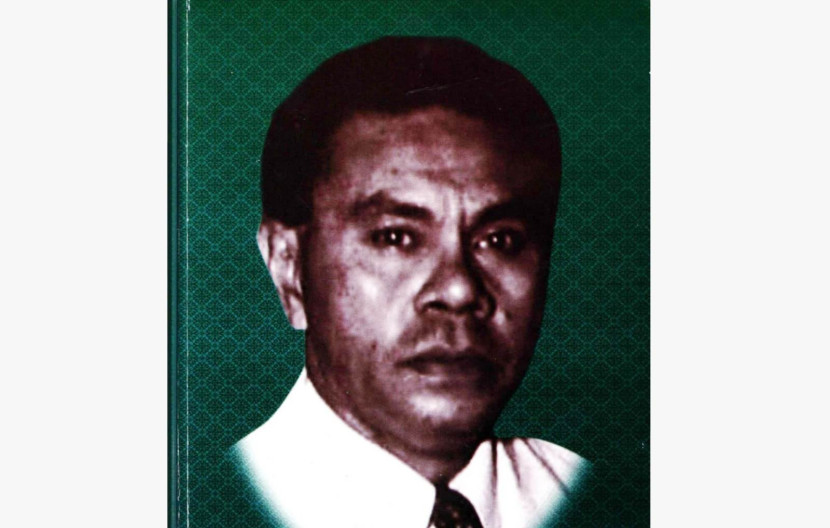
Pagi-pagi, 18 Agustus 1945 Moh Hatta mengumpulkan beberapa orang sebelum rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) karena opsir Jepang memberi tahu Hatta bahwa orang-orang Kristen Indonesia Timur keberatan dengan tujuh kata dari Pancasila di Piagam Jakarta yang akan dimasukkan ke Pembukaan UUD. Opsir itu minta dihapus saja demi persatuan.
Pagi itu, jadwal pembukaan rapat PPKI molor, karena harus ada lobi-lobi kepada tokoh-tokoh Islam. Tokoh-tokoh Islam menyetujui usulan baru: Berketuhanan Yang Maha Esa, mengganti: Berdasarkan Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Pada rapat-rapat BPUPKI, Latuharhary, orang Maluku oertama yang meraih sarjana hukum di Belanda, termasuk yang keberatan dengan tujuh kata itu. Lalu mengapa sejarawan Australia, Richard E Elson berkesimpulan “bahwa perubahan yang direkayasa oleh Hatta pada 18 Agustus 1945, bersifat panik dan tidak perlu”?
Menurut Elson, “Perubahan tersebut memberi kaum Islamis kesempatan untuk menciptakan narasi yang tampak kredibel dan, secara episodik, bermanfaat secara politis tentang viktimisasi, diskriminasi, dan penindasan negara.”
Elson mengeluarkan pernyataan itu pada 2009 lewat tulisannya “Another Look at The Jakarta Charter Controversy”. Ia menguraikan panjang lebar perdebatan yang sudah muncul di rapat-rapat BPUPKI mengenai tujuh kata itu.
Namun, keputusan BPUPKI akhirnya tetap memakai tujuh kata itu, sebab itu sudah menjeadi kesepakatan kalangan nasionalis Islam dan nasionalis kebangsaan pada 11 Juni 1945 lewat Panitia Sembilan setelah perdebatan-perdebatan pada Mai 1945 merembet pada usulan pembentukan negara Islam.
Pada 1 Juni 1945, Sukarno menyudahi perdebatan lewat pidatonya yang kemudian dikenang sebagai Hari Lahir Pancasila. “Kita hendak mendirikan suatu negara ‘semua buat semua’. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun dolongan yang kaya, --tetapi ‘semua buat semua’,” ujar Sukarno seperti tercatat dalam Risalah Sidang-Sidang BPUPKI – PPKI.
Panitia Sembilan kemudian bekerja, yang kemudian melahirkan Piagam Jakarta yang didalamnya ada tujuh kata yang di kemudian hari diperdebatkan lagi. Bahkan, Jepang sebagai penguasa di Indonesia Timur merasa perlu melobi Hatta, agar tujuh kata itu dihapus demi menjaga persatuan bangsa.
Namun, setelah dihapus, toh orang-orang Kristen dari Minahasa dan Ambon tetap tidak mau bergabung dengan Republik Indonesia. Orang-orang Maluku di Jakarta membentuk Persatuan Timur Besar (PTB) tak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Disusul kemudian, di Minahasa lahir Twapro.
PTB dan Twapro menginginkan Sulawesi Utara sebagai provinsi ke-12 dari Kerajaan Belanda dan Maluku sebagai provinsi ke-13 dari Kerajaan Belanda. Artinya, penghapusan tujuh kata “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” tidak efektif mencegah perpecahan.
Pada saat terjadi perdebatan di BPUPKI, Tak hanya Latuharhary dari Maluku yang keberatan dengan tujhh kata itu. Ada juga Wongsonegoro dan Hussein Djajadiningrat yanag keberatan.
Tapi, Piagam Jakarat yang memuat tujuh kata itu disepakati oleh Maramis dari Minahasa, satu-satunya tokoh Kristen dari Timur. Panitia Sembilan terdiri dari Sukarno: (Ketua), Mohammad Hatta:(Wakil Ketua), Mr AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdoel Kahar Moezakir, H Agus Salim, Mr Achmad Soebardjo, KH Wahid Hasyim, dan Mohammad Yamin.
Pada saat menjadi anggota BPUPKI, Latuharhary ditunjuk untuk mewakili orang Maluku di Jawa. Namun, ketika menjadi anggota PPKI, ia ditunjuk sebagai wakil dari Maluku.
Maka, hal-hal yang dibahas di BPUPKI/PPKI ia informasikan kepada orang-orang Maluku. Pada saat Sukarno-Hatta pergi Saigon untuk membahas kemerdekaan dengan Jenderal Terauchi, panglima perang Jepang di Asia Tenggara, orang-orang Maluku di Jawa berkumpul.